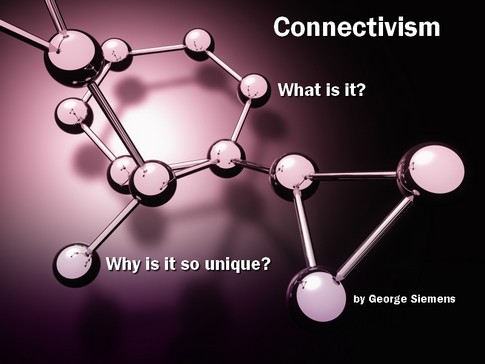
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembelajaran interaktif setting
kooperatif adalah cara mengajar dengan mengaktifkan siswa dalam mengemukakan
pemikirannya dan guru aktif untuk membimbing siswa sehingga siswa dilibatkan
dalam proses belajar. Pembelajaran interaktif yang dimaksud yaitu dengan
memberikan bentuk latihan di mana tejadi
diskusi antara guru dengan siswa
sehingga tejalin suasana belajar yang harmonis. Setting kooperatif
merupakan sarana yang digunakan
untuk mempermudahkan capaian pembelajaran interaktif setting kooperatif
berhubungan dengan pengelolaan kelas berupa pengelompokan siswa sesuai dengan
pembelajaran kooperatif, yaitu suatu pendekatan yang mencapai suatu kelompok
kecil dari siswa
yang bekerjasama dalam satu tim, mempunyai kemampuan akademik
yang beragam untuk
menyelesaikan masalah-masalah, melengkapi tugas/ menyelesaikan suatu
tujuan bersama.
Siswa merupakan bagian utama dalam
kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa dituntut secara aktif memproses dan
mengelola perolehan belajar, untuk itu siswa dituntut untuk aktif secara fisik,
intelektual dan emosional. Implikasi
keaktifan bagi siswa terwujud
perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan menganalisa
hasil dan ingin tahu implikasinya. Implikasi keaktifan bagi seorang guru
sebagai pengelola dan penyelenggara dari belajar mengajar adalah memberi
kesempatan belajar kepada siswa.
Thorndike (1874-1949), ia mengemukakan
teorinya yang disebut sebagai teori belajar “Connectionism” karena belajar
merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori
ini sering juga disebut “Trial and error” dalam rangka
menilai respon yang terdapat bagi stimulus tertentu. Thorndike mendasarkan
teorinya atas hasil-hasil penelitiannya terhadap tingkah laku beberapa binatang
antara lain kucing, dan tingkah
laku anak-anak dan orang dewasa. Ia mengatakan, bahwa
belajar dengan “Trial and error” itu dimulai dengan adanya beberapa motif yang
mendorong keaktifan. Dengan demikian, untuk mengaktifkan anak
dalam belajar dibutuhkan
motivasi.
Menjadikan model connectivism untuk
meningkatkan pemecahan masalah keterampilan belajar siswa, menjadi model
pelajaran yang menarik dan membantu tugas guru dalam meningkatkan efektivitas
pembelajaran. Maka diperlukan suatu model pembelajaran yang inovatif dengan
setting kooperatif. Salah satu model
pembelajaran yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang terencana yang
disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk membantu siswa
menguasai tujuan pembelajaran yang spesifik adalah model pembelajaran
connectivism untuk meningkatkan pemecahan masalah keterampilan belajar siswa.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah
disampaikan, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan dalam makalah ini
adalah sebagai berikut:
1.
Apakah yang dimaksud dengan
model pembelajaran connectivism?
2. Apakah
yang dimaksud dengan teori chaos?
3. Bagaimanakah
hubungan teori chaos dengan model pembelajaran connectivism?
4.
Bagaimanakah penerapan model
pembelajaran connectivism dalam
meningkatkan keterampilan belajar siswa?
C. Tujuan
Adapun tujuan yang dapat disampaikan
dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1.
Untuk mendeskripsikan model
pembelajaran connectivism.
2.
Untuk mendeskripsikan
pengertian teori chaos.
3.
Untuk mendeskripsikan
hubungan teori chaos dengan model pembelajaran connectivism.
4.
Untuk mengetahui penerapan
model pembelajaran connectivism dalam meningkatkan keterampilan belajar siswa.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Model Pembelajaran Connectivism
Istilah Connectivism
diperkenalkan
pertama kali oleh George Siemens.
Connectivism
merupakan teori pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip prinsip yang digali melalui teori
teori chaos, jejaring, kompleksitas (complexity), dan self-organizing.
Pembelajaran dalam pengertian Connectivism dipahami sebagai suatu proses yang terjadi
dalam lingkungan-lingkungan perubahan
elemen-elemen inti pembelajaran
yang kabur dan tidak sepenuhnya
dalam kendali
seorang
individu. Dalam Connectivism, pembelajaran yang
didefinisikan sebagai: Kegiatan dimulai dari kegiatan
mengetahui sampai
dengan kegiatan
menciptakan pengetahuan yang dapat ditindakkan (actionable knowledge).
Connectivism adalah integrasi prinsip-prinsip dieksplorasi
oleh kekacauan,
jaringan, dan kompleksitas
dan self-organisasi teori. Belajar adalah proses yang terjadi dalam lingkungan samar-samar dari pergeseran elemen inti - tidak sepenuhnya di bawah
kendali individu. Belajar
(didefinisikan
sebagai pengetahuan
ditindak lanjut) dapat
berada di luar diri kita (dalam suatu
organisasi atau database), difokuskan pada menghubungkan set
informasi khusus, dan koneksi yang memungkinkan kita
untuk mempelajari
lebih lanjut
lebih penting daripada negara kita saat mengetahui.
Connectivism didorong oleh pemahaman bahwa keputusan didasarkan pada
mengubah dengan cepat. Informasi baru
terus diakuisisi. Kemampuan untuk
menarik perbedaan
antara informasi yang
penting dan tidak penting sangat
penting. Kemampuan untuk
mengenali kapan informasi baru
mengubah
lanskap berdasarkan keputusan yang dibuat sebelumnya yang dirasa juga
sangat penting.
Kegiatan ini dapat terjadi di luar diri manusia (dalam suatu organisasi, suatu
database, dan lain sebagainya). Kegiatan
ini
berfokus pada penghubungan kumpulan-kumpulan informasi khusus, dan hubungan hubungan
lain yang memungkinkan kita belajar lebih banyak. Karena itu, kemampuan
melakukan penghubungan-penghubungan ini merupakan hal
yang lebih penting dari pengetahuan
yang kita kuasai.
Connectivism dilandasi oleh pemahaman
akan
kenyataan bahwa pengambilan
keputusan
di
era informasi akan
didasarkan pada landasan-landasan
yang berubah dengan cepat. Informasi-informasi baru akan diperoleh secara terus
menerus secara berkelanjutan. Kemampuan membedakan informasi yang penting dan yang tidak
penting dengan
demikian
bersifat vital. Dan
juga, kemampuan untuk mengenali kapan
suatu
informasi baru
telah mengubah
landasan
yang menjadi dasar keputusan keputusan yang diambil kemarin merupakan
hal
yang sangat kritis sifatnya (critical).
a)
Prinsip-prinsip Model Pembelajaran Connectivism
Model pembelajaran connectivism
dinilai dapat membentuk siswa agar mampu berpikir lebih kritis dalam menerima
informasi-informasi yang didapatkannya di dalam belajar. Dengan
demikian model pembelajaran connectivism berkembang dengan prinsip-prinsip yang
berlaku sampai dengan saat ini sebagai berikut:
1. Pembelajaran
dan pengetahuan berada dalam keaneka-ragaman (diversity)
pandangan/pendapat/opini.
2. Pembelajaran
merupakan suatu proses menghubungkan sumber sumber informasi terutama node node
khusus. Selain itu, pembelajaran dapat terjadi di luar diri manusia ( may
reside in non-human appliances )
3. Kapasitas
untuk dapat mengetahui lebih penting dari pada apa yang saat ini diketahui.
4. Mendorong
dan memelihara hubungan hubungan diperlukan untuk memfasilitasi terjadinya
pembelajaran berkelanjutan.
5. Kemampuan
untuk melihat hubungan hubungan antara bidang bidang, ide ide, dan konsep
konsep merupakan keterampilan inti.
6. Kemutakhiran
( akurat, pengetahuan up-to-date ) merupakan tujuan dari kegiatan pembelajaran
connectivism
7. Pengambilan
keputusan merupakan proses pembelajaran.
8. Memilih
apa yang akan dipelajari sangat penting dalam menghadapi “banjir informasi”.
- Makna
dari informasi yang masuk harus dilihat melalui “kacamata” suatu
pergeseran realitas. Suatu jawaban yang benar saat ini dapat salah besok
pagi karena adanya perubahan “iklim” informasi yang mempengaruhi keputusan
tersebut.
b) Implikasi Penggunaan Teori Connectivism
Model pembelajaran connectivism mempunyai implikasi terhadap semua aspek kehidupan.
Selain pada proses pembelajaran, terdapat implikasi juga terhadap aspek-aspek
lain sebagai berikut:
1.
Manajemen dan kepemimpinan. Menyadari
bahwa pengetahuan yang lengkap tidak mungkin didapat dari pemikiran satu orang,
maka diperlukan ancangan berbeda dalam menilai suatu situasi. Pembentukan
berbagai tim yang berbeda pandangan merupakan struktur yang penting dan
diperlukan dalam rangka agar dapat menggali ide ide secara lengkap. Inovasi
merupakan tantangan tambahan. Suatu ide yang dianggap revolusioner hari ini
suatu saat akan ada sebagai elemen yang biasa. Kemampuan suatu organisasi untuk
mendorong, membina, dan mensistesiskan dampak dampak dari berbagai pandangan
atas suatu informasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka survival di
era ekonomi-pengetahuan.
- Organisasi
penyediaan jasa media-masa, berita, informasi, ditantang untuk terbuka,
real-time, dan melakukan blogging agar terjadi komunikasi dua arah.
- Keterkaitan
yang bertambah erat antara manajemen pengetahuan individu dengan manajemen
pengetahuan organisasi.
- Desain
dari lingkungan pembelajaran.
c) Hal-hal Yang Diperoleh dari Penggunaan Model Pembelajaran Connectivism
Dalam proses pembelajaran, hal-hal yang
dapat kita peroleh atau yang dapat kita petik dari penggunaan model
pembelajaran connectivism ini adalah sebagai berikut:
1.
Saluran (conduit, pipe) untuk terhubung dengan jejaring lebih penting dari
apa yang terdapat dalam saluran dan jejaring itu. Hal ini disebabkan apa yang
ada dalam jejaring akan selalu berubah dengan cepat, sedanglan saluran (bahasa,
media, teknologi) bersifat lebih permanen. Kemampuan kita untuk belajar apa
yang kita butuhkan di masa depan lebih penting dari yang kita ketahui hari ini.
- Tantangan
nyata dari suatu teori pembelajaran adalah kemampuan untuk mengaktualisasi
pengetahuan yang dikuasai pada titik penerapannya. Dan ketika suatu
pengetahuan dibutuhkan namun ternyata belum dikuasai, maka kemampuan untuk
“mencebur” ke dalam sumber pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan yang
diperlukan merupakan keterampilan yang bersifat vital.
- Karena
pengetahuan berevolusi dan berkembang secara berkesinambungan, akses
kepada apa yang diperlukan lebih penting dari apa yang dikuasai saat ini.
- Connectivism
merupakan model pembelajaran yang menjawab “pergeseran tektonik” dalam
masyarakat di mana pembelajaran bukan lagi suatu kegiatan intern
individual. Cara manusia bekerja dan berfungsi dalam masyarakat berubah
dengan dipakainya alat alat (tools) baru yang dibuka peluangnya oleh
kemajuan ICT.
- Bidang
pendidikan terlalu lambat dalam mengenali dan beradaptasi dengan dampak
dari adanya alat alat pembelajaran yang baru, perubahan perubahan
lingkungan pembelajaran, dan arti baru dari pembelajaran.
- Connectivism
menawarkan keterampilan belajar bagi para pembelajar berupa kegiatan
kegiatan yang diperlukannya untuk menikmati hidup di era digital.
B.
Teori Chaos
Kusmarni (2008) menyatakan bahwa chaos
menunjukkan ketidakberaturan, kekacauan, keacakan atau kebetulan, yaitu:
gerakan acak tanpa tujuan, kegunaan atau prinsip tertentu. Alam semesta yang
bersifat dinamis ini kelihatannya bekerja melalui system yang linier, tetapi
banyak juga yang tidak bekerja secara linier dan tidak dapat dipahami melalui
system linier, seperti awan, pohon, garis pantai, ombak dan lain sebagainya,
yang secara sekilas menampakkan acak dan tidak teratur. Sistem seperti inilah
yang dinamakan dengan teori chaos, yaitu suatu teori yang berkaitan dengan
proses alam yang nampaknya kacau, acak dan tidak linier (system yang tidak
dapat diprediksi berdasarkan kondisi awal).
Teori chaos dalam bidang pendidikan
memberikan wawasan mengenai sistem pendidikan yang terdiri dari dunia mekanis.
Pendidikan di era manapun bagaimanapun didasarkan pada kebutuhan era tersebut.
Dalam dunia pendidikan teori chaos ini akan memberikan tantangan kepada
pebelajar untuk lebih memahami pola-pola pembelajaran yang timbul. Kondisi
chaos membuat hilangnya kemampu-prakiraan (predictability), karena adanya
urutan atau susunan yang rumit yang bertentangan dengan keteraturan. Tidak sama
dengan paham konstruktivisme yang menyatakan bahwa para peserta didik memahami
sesuatu dengan membuat pemaknaan. Sedangkan chaos menyatakan bahwa pemaknaan
itu telah ada dan memiliki tantangan yang jelas bagi peserta didik untuk
mengenali pola-pola yang tersembunyi (Surya, 2009).
C. Hubungan Teori
Chaos dengan Model Pembelajaran Connectivism
Perkembangan ilmu pengetahuan tidak
semuanya menunjukkan gerak linier atau melingkar, tetapi juga ada yang bersifat
non-linier. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang diakibatkan
oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung dengan
“lompatan-lompatan” yang mengejutkan, sehingga membutuhkan kreativitas
masyarakat untuk mencari alternatif-alternatif jawaban dalam memecahkan
permasalahannya. Katherine Hayles mengemukakan bahwa ketimpangan dalam kemajuan
ilmu-ilmu pengetahuan bila dibandingkan dengan kemajuan ilmu-ilmu sosial dan
humaniora, telah menyebabkan banyak persoalan kemanusiaan yang tidak
terselesaikan. Kemajuan ilmu dan teknologi telah menghasilkan dampak negatif
seperti penghabisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, polusi dalam
berbagai bentuk dan melebarnya lubang ozon. Serta permasalahan dalam
aspek-aspek moral, pandangan hidup, agama, hubungan-hubungan social, bahasa dan
komunikasi, seni dan budaya. Oleh karena itu kemajuan ilmu dan teknologi telah
melahirkan suatu dikotomi dan dilema bagi umat manusia.
Sistem chaos merupakan salah satu “jembatan” untuk mengatasi
kesenjangan ilmu pengetahuan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti
etika, sastra, seni atau agama dalam memperjelas kehidupan manusia. Sehingga
ilmu pengetahuan dapat berkembang secara “selaras” dan “memanusiakan manusia”
menuju umat manusia yang lebih maju sekaligus beradab. Melalui sebuah kondisi
chaos terjadi inovasi dan penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dengan
menyelaraskan, menyeimbangkan dan menyilangkan antara ilmu pengetahuan dengan
etika, sastra, seni atau agama.
Berkaitan dengan hal tersebut teori chaos memberikan pengaruh yang besar
dalam penerapan model pembelajaran connectivism.
Dengan adanya keterkaitan antara teori chaos dengan model pembelajaran connectivism, akan memberikan dampak
dimasa yang akan datang nantinya. Model pembelajaran connectivism mengarahkan siswa untuk dapat berpikir kritis dan
kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran didalam kelas, sedangkan dengan
teori chaos yang dikaitkan dengan model pembelajaran connectivism menuntun siswa untuk menuntun siswa untuk mengerahkan
pemikiran kritis yang masih bersifat acak dan tidak beraturan menjadi sebuah
pola-pola berpikir yang lebih tersusun rapi dan sistematis.
D. Model Pembelajaran Connnectivism untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa
Keterampilan belajar ini sangat
menentukan bagi siswa untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Setiap
siswa dalam belajar selalu memiliki keterampilannya dalam belajar, melalui keterampilan
tersebut akan terlihat siswa mana saja yang dapat mengikuti proses pembelajaran
dengan baik. Namun tidak bisa dipungkiri, didalam setiap kelas terdapat
beberapa orang siswa yang mampu memperoleh hasil yang memuaskaan dalam proses
pembelajaran karena memiliki keterampilan belajar yang bagus didalam dirinya,
dan ada juga siswa yang mengalami permasalahan pada hasil belajarnya meskipun
selalu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Hal tersebut diakibatkan
bukan karena siswa malas belajar tetapi diakibatkan oleh keterampilan belajar
siswa tersebut yang kurang maksimal, sehingga perlu adanya upaya untuk
meningkatkan keterampilan belajarnya.
Model pembelajaran connectivism merupakan model pembelajaran yang menekan pada
pengambilan keputusan secara cepat oleh siswa, kegiatan tersebut dibutuhkan
untuk melatih siswa dalam proses belajar mandiri di dalam maupun diluar kelas.
Kegiatan yang dimaksudkan adalah “Kegiatan
dimulai dari kegiatan
mengetahui sampai
dengan kegiatan
menciptakan pengetahuan yang dapat ditindakkan”. Hal tersebut dimaksudkan bahwa dengan
pengunaan model connectivism ini
siswa diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran dikelas dari kegiatan
mengetahui materi pelajaran apa yang akan mereka pelajari hinggga sampai
menciptakan pengetahuan baru dari hasil belajarnya.
Model
pembelajaran connectivism mengarahkan
siswa untuk mampu mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkannya dalam
belajar secara cepat dan tepat, dimana pada era digital saat ini infromasi
telah banyak dapat diperoleh melalui internet ataupun e-book. Hal ini tentunya akan sangat membantu bagi siswa dalam
meningkatkan keterampilan belajarnya untuk meningkatkan hasil belajarnya.
Terlebih lagi pada saat ini telah diputuskan bahwa siswalah yang lebih aktif
dalam proses pembelajaran dikelas maupun diluar kelas (student centered), sehingga siswa akan lebih diarahkan untuk
belajar secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi dan sumber belajar yang
ada disekitarnya dengan dipandu oleh guru sebagai fasilitatornya dalam blajar.
Penggunaan
model pembelaran connectivism sangat
dibutuhkan untuk menngembangkan daya berpikir kritis siswa dalam belajar. Siswa
akan terlatih dalam mengambil keputusan secara cepat dalam menghadapi
permasalahan yang ditemukannya dan terbiasa mengumpulkan informasi-informasi
yang penting mengenai materi pembelajaran maupun hal lainnya yang mendukung
dirinya sendiri untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi. Model
pembelajaran connectivism ini dapat diimplementasikan sebaik mungkin oleh guru
dalam membantu dan menunjang proses pembelajaran dikelas agar lebih efektif dan
lebih bisa menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered).
E.
Konsep
Diri
1.
Pengertian Konsep Diri
Menurut Para Ahli adalah sebagai berikut :
a. Menurut Burns (dalam
Pudjijogyanti, 1993)
Konsep diri adalah hubungan antara sikap dan keyakinan
tentang diri kita sendiri.
b.
Menurut Rini (dalam Pudjijogyanti 2004)
Konsep diri diartikan keyakinan, pandangan atau penilaian seseorang
terhadap dirinya.
c.
Menurut Cawagas (dalam Pudjijogyanti, 1993)
Konsep diri mencangkup seluruh
pandangan individu akan dimensi fisik, karakteristik pribadi, motivasi,
kelemahan, kepandaian, kegagalan dan lain sebagainya.
d.
Menurut William D Brooks (dalam Rahmat,
2003)
Konsep diri sebagai “ those physical, social, and psychological
perceptions of ourselves that we have derived from experiences and our
interaction with others”. Jadi, konsep diri adalah pandangan perasaan tentang
diri kita. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologi, sosial dan
fisik.
e. Menurut
Pietrosefa (2002)
Pietrosefa memberikan gambaran mengenai
konsep diri yang diadaptasikan oleh Mappiarre yaitu ;
1. Dimensi Pertama Citra Diri, yaitu diri
dilihat oleh diri sendiri.
2. Dimensi Kedua Ctra Diri, yaitu dilihat oleh orang lain, persepsi orang lain terhadap dirinya.
3. Dimensi Ketiga Citra Diri, yaitu diri
mengacu pada tipe-tipe orang yang saya kehendaki tentang diri saya (ideal
self).
Sedangkan Konsep diri yang bersifat psikologis berdasarkan pikiran,
perasaan dan emosional. Hal ini berhubungan dengaan kualitas dan abilitas yang
memainkan peranan penting dalam penyesuaian dalam kehidupan, seperti
keberanian, kejujuran, kemandirian, kepercayaan diri, aspirasi dan kemampuan
diri dari tipe-tipe yang berbeda, yaitu:
1.
Konsep diri merupakan
gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya, meliputi karakteristik fisik,
sosial, psikologis, emosional, aspirsi daan prestasi ( Hurlock).
2.
Konsep diri adalah
pandangan dan perasaan individu tentang dirinya sendiri yang dapat bersifat
psikiologis, sosial dan fisik (Brooks).
3.
Konsep diri adalah
pengetahuan dan evaluasi terhadap diri sendiri yang diperoleh melalui
pengalaman dari interaksi dengan orang lain (burns).
Konsep diri
mulai terbentuk dan berkembang begitu manusia lahir. Soeitoe menyatakan konsep
diri seseorang terbentuk dari pengalaman sendiri dari uraian yang diberikan
oleh orang lain tentang dirinya. Pengalaman sendiri dan informasi dari
lingkungan terintegrasi kedalam konsep diri.
Konsep diri
merupakan faktor bawaan tapi dibentuk dan berkembang melalui proses belajar
yaitu dari pengalaman-pengalaman individu dalam interaksinya dengan orang lain.
Individu dengan konsep diri yang tinggi lebih banyak memiliki pengalaman yang
menyenangkan dari pada individu dengan konsep diri yang rendah.
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah
kesadaran akan pandangan , pendapat, penilaian, dan sikap seseorang terhadap
dirinya sendiri yang meliputi fisik, diri pribadi, diri keluarga, diri sosial
juga etika.
F. Komponen Konsep Diri
Komponen-komponen
konsep diri menurut Hurlock (1976) antara lain:
a. The Perceptual Component
Gambaran dan kesan seseorang
tentang penampilan tubuhnya dan kesan yang dibuat pada orang lain atau sering
disebut konsep diri fisik. Tercangkup didalamnya gambaran yang dipunyai
seseorang tentang daya tarik tubuhnya (attractiveness) dan keserasian jenis
kelamin (sex apporiateness). Komponen ini sering disebut physical self concept.
b. The Conseptual Component
Pandangan tentang
karakteristik yang berbeda dengan orang lain baik tentang dengan kemampuan dan
kekurangnya serta disusun dari kualitas penyesuaian hidupnya tentang
kepercayaan diri tergantung keberanian, kegagalan dan kelemahan. Komponen ini
sering disebut psychological self concept.
c. The Attitudinal Component
Perasaan tentang kebangaan dan
rasa malunya. Yang termasuk dalam komponen ini adalah keyakinan nilai, aspirasi
dan komitmen yang membentuk dirinya.
Sedangkan menurut Pudjijogyanti (1988), Komponen-komponen konsep diri ada
dua yaitu :
1.
Komponen Kognitif
Komponen kognitif merupakan
pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. Misalnya “ saya anak bodoh “ atau
“ siapa saya “. Jadi komponen kognitif merupakan penjelasan dari “siapa saya”
yang akan member gambaran tentang diri saya. Gambaran diri ( self-picture ) tersebut akaan membentuk citra diri (
self-image ).
2.
Komponen Afektif
Komponen afektif merupakan
penilaian individu terhadap diri. penilaian tersebut akan membentuk penerimaan
terhadap diri ( self acceptance ), serta harga diri ( self-esteem) individu.
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri
Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi pembentukan dan perkembangan konsep diri, antara lain:
1. Usia
Konsep diri terbentuk seiring dengan bertambahnya usia, dimana perbedaan
ini lebih banyak berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan. Pada masa
kanak-kanak, konsep diri seseorang menyangkut hal-hal disekitar diri dan
keluarganya. Pada masa remaja, konsep diri sangat dipengaruhi oleh teman sebaya
dan orang yang dipujanya. Sedangkan remaja yang kematangannya terlambat, yang
diperlakukan seperti anak-anak, merasa tidak dipahami sehingga cenderung
berperilaku kurang dapat menyesuaikan diri. Sedangkan masa dewasa konsep
dirinya sangat dipengaruhi oleh status sosial dan pekerjaan, dan pada usia tua
konsep dirinya lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan fisik, perubahan mental
maupun social.
2. Inteligens
Inteligensi
mempengaruhi penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya, orang lain dan
dirinya sendiri. Semakin tinggi taraf intreligensinya semakain baik penyesuaian
dirinya dan lebih mampu bereaksi terhadap rangsangan lingkungan atau orang lain
dengan cara yang dapat diterima. Hal ini jelas akan meningkatkan konsep
dirinya, demikian pula sebaliknya (Syaiful, 2008).
3. Pendidikan
Seseorang
yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan prestisenya.
Jika prestisenya meningkat maka konsep dirinya akan berubah (Syaiful, 2008).
4. Status Sosial Ekonomi
Status
sosial seseorang mempengaruhi bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya.
Penerimaan lingkungan dapat mempengaruhi konsep diri seseorang. Penerimaan
lingkungan terhadap seseorang cenderung didasarkan pada status sosial
ekonominya. Maka dapat dikatakan individu yang status sosialnya tinggi akan
mempunyai konsep diri yang lebih positif dibandingkan individu yang status
sosialnya rendah.
Hal ini
didukung oleh penelitian Rosenberg terhadap anak-anak dari ekonomi sosial
tinggi menunjukkan bahwa mereka memiliki konsep diri yang tinggi dibandingkan
dengan anak-anak yang berasal dari status ekonomi rendah. Hasilnya adalah 51 %
anak dari ekonomi tinggi mempunyai konsep diri yang tinggi. Dan hanya 38 % anak
dari tingkat ekonomi rendah memiliki tingkat konsep diri yang tinggi (dalam
Skripsi Darmayekti, 2006:21).
5.
HubunganKeluarga
Seseorang
yang mempunyai hubungan yang erat dengan seorang anggota keluarga akan
mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan ingin mengembangkan pola
kepribadian yang sama. Bila tokoh ini sesama jenis, maka akan tergolong untuk
mengembangkan konsep diri yang layak untuk jenis seksnya.
6.
Orang Lain
Kita
mengenal diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Bagaimana anda
mengenal diri saya, akan membentuk konsep diri saya. Sullivan (dalam Rakhmat,
2005:101) menjelaskan bahwa individu diterima orang lain, dihormati dan
disenangi karena keadaan dirinya, individu akan cenderung bersikap menghormati
dan menerima dirinya. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan dirinya,
menyalahkan dan menolaknya, ia akan cenderung tidak akan menyenangi dirinya.
Miyamoto dan Dornbusch (dalam Rakhmat, 2005:101) mencoba mengkorelasikan
penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri dengan skala lima angka dari yang
palin jelek sampai yang paling baik. Yang dinilai adalah kecerdasan,
kepercayaan diri, daya tarik fisik, dan kesukaan orang lain terhadap dirinya.
Dengan skala yang sama mereka juga menilai orang lain. Ternyata, orang-orang
yang dinilai baik oleh orang lain, cenderung memberikan skor yang tinggi juga
dalam menilai dirinya. Artinya, harga diri sesuai dengan penilaian orang lain
terhadap dirinya.
7.
Kelompok Rujukan (Reference Group)
Yaitu
kelompok yang secara emosional mengikat individu, dan berpengaruh terhadap
perkembangan konsep dirinya. Menurut Brooks dan Emmert (dalam Rakhmat,
2005:105), ciri orang yang memiliki konsep diri negatif ialah peka terhadap
kritik, responsif sekali terhadap pujian, mempunyai sikap hiperkritis,
cenderung merasa tidak disenagi orang lain, merasa tidak diperhatikan, dan
bersikap pesimis terhadap kompetisi.
Sebaliknya, orang yang memilikii konsep diri positif ditandai dengan lima hal:
Sebaliknya, orang yang memilikii konsep diri positif ditandai dengan lima hal:
1. Kemampuan mengatasi masalah.
2. Merasa setara dengan orang lain.
3. Menerima pujian tanpa rasa malu.
4. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai
berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui
masyarakat.
5. Mampu memperbaiki dirinya karena ia
sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan
berusaha mengubahnya.
H. Manfaat Konsep Diri
1.
Rasa Percaya Diri
Bila anda mengetahui potensi
diri anda, maka anda akan lebih percaya diri, dan inilah kunci utama
keberhasilan seseorang.
2.
Semangat dan Gairah Hidup
Kalau anda mengetahui potensi
diri anda, anda akan hidup lebih bersemangat dan penuh gairah.
3.
Keberanian
Ketika rasa percaya diri itu
tumbuh, anda akan berani merealisasikan apa yang telah menjadi tujuan dan
sasaran hidup anda. Anda akan berani mengambil resiko.
4.
Kebebasan
Ketika anda telah menemukan
potensi diri serta merasa percaya diri, anda akan merasa hidup lebih bebas,
bebas dari ketakutan dan keraguan.
5.
Harga Diri ( Self-Esteem )
Bila anda
menerima keberadaan diri anda, menerima kelebihan maupun kekurangan diri anda,
anda akan mencintai diri anda. Rasa cinta pada diri sendiri inilah yang menjadi
landasan untuk menjadi diri sendiri. Dan ketika anda mampu menjadi diri
sendiri, maka self-esteem anda akan meningkat.
6.
Kedamaian dan Kebahagiaan
Dengan
menemukan siapa diri anda – menemukan citra-citra yang memadai, realistik dan
positif – pintu kebebasan terbuka untuk anda, dimana anda akan bisa merasakan
kedamaian dan kebahagiaan. Anda bisa bahagia dengan keberadaan diri anda
sendiri.
7.
Keberhasilan dalan hidup
Kunci
keberhasilan dalam hidup adalah percaya pada diri sendiri, untuk mempercayai
diri sendiri, kita perlu menggali dari dalam diri untuk menemukan potensi diri
yang tersembunyi.
Dengan membangun citra diri yang memadai, realistik dan positif,
sesungguhnya anda membangun jalan keberhasilan diri anda sendiri.
I. Hambatan Dalam
Membangun Konsep Diri
Potensi yang dimiliki seseorang bisa berkembang atau tidak, itu tergantung
pada pribadi yang bersangkutan dan lingkungan dia berada. Beberapa hambatan
yang sering terjadi dalam pengembangan potensi diri adalah sebagai berikut:
1.
Hambatan yang berasal dari
lingkungan
Lingkungan
merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengembangan potensi diri.
Hambatan ini antara lain disebabkan sistem pendidikan yang dianut, lingkungan
kerja yang tidak mendukung semangat pengembangan potensi diri, dan tanggapan
atau kebiasaan dalam lingkungan kebudayaan.
2.
Hambatan yang berasal dari individu sendiri
Penghambat
yang cukup besar adalah pada diri sendiri,misalnya sikap berprasangka, tidak
memiliki tujuan yang jelas, keengganan mengenal diri sendiri, ketidak mampuan
mengatur diri, pribadi yang kerdil, kemampuan yang tidak memadai untuk
memecahkan masalah, kreativitas rendah, wibawa rendah, kemampuan pemahaman
manajerial lemah, kemampuan latih rendah dan kemampuan membina tim yang rendah.
J.
Konsep
Diri Positif dan Negative
Konsep diri merupakan faktor
penting didalam berinteraksi. Hal ini disebabkan oleh setiap individu dalam
bertingkah laku sedapat mungkin disesuaikan dengan konsep diri. Kemampuan manusia bila dibandingkan
dengan mahluk lain adalah lebih mampu menyadari siapa dirinya, mengobservasi
diri dalam setiap tindakan serta mampu mengevaluasi setiap tindakan sehingga
mengerti dan memahami tingkah laku yang dapat diterima oleh lingkungan.
Dengan demikian
manusia memiliki kecenderungan untuk menetapkan nilai-nilai pada saat mempersepsi
sesuatu. Setiap individu dapat saja menyadari keadaannya atau identitas yang
dimilikinya akan tetapi yang lebih penting adalah menyadari seberapa baik atau
buruk keadaan yang dimiliki serta bagaimana harus bersikap terhadap keadaan
tersebut. Tingkah laku individu sangat bergantung pada kualitas konsep dirinya
yaitu konsep diri positif atau konsep diri negatif. Menurut Brooks
dan Emmart (1976), orang yang memiliki konsep
diri positif menunjukkan karakteristik sebagai berikut:
1. Konsef diri positif
a. Merasa
mampu mengatasi masalah. Pemahaman diri terhadap kemampuan subyektif untuk
mengatasi persoalan-persoalan obyektif yang dihadapi.
b. Merasa
setara dengan orang lain. Pemahaman bahwa manusia dilahirkan tidak dengan
membawa pengetahuan dan kekayaan. Pengetahuan dan kekayaan didapatkan dari
proses belajar dan bekerja sepanjang hidup. Pemahaman tersebut menyebabkan
individu tidak merasa lebih atau kurang terhadap orang lain.
c. Menerima pujian tanpa rasa malu. Pemahaman
terhadap pujian, atau penghargaan layak diberikan terhadap individu berdasarkan
dari hasil apa yang telah dikerjakan sebelumnya.
d. Merasa
mampu memperbaiki diri. Kemampuan untuk melakukan proses refleksi diri untuk
memperbaiki perilaku yang
dianggap kurang.
2. Konsep diri negatif
a.
Peka terhadap kritik. Kurangnya kemampuan
untuk menerima kritik dari orang lain sebagai proses refleksi diri.
b.
Bersikap responsif terhadap pujian.
Bersikap yang berlebihan terhadap tindakan yang telah dilakukan, sehingga
merasa segala tindakannya perlu mendapat penghargaan.
c.
Cenderung merasa tidak disukai orang lain.
Perasaan subyektif bahwa setiap orang lain disekitarnya memandang dirinya
dengan negatif.
d.
Mempunyai sikap hiperkritik. Suka melakukan
kritik negatif secara berlebihan terhadap orang lain.
e.
Mengalami hambatan dalam interaksi dengan
lingkungan sosialnya. Merasa kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang-orang
lain.
K. Langkah-Langkah Mempertahankan Konsep Diri
Langkah-langkah mempertahankan konsep diri yaitu sebagai berikut :
1.
Bersikap obyektif dalam mengenali diri
sendiri
Jangan
abaikan pengalaman positif atau pun keberhasilan sekecil apapun yang pernah
dicapai. Lihatlah talenta, bakat dan potensi diri dan carilah cara dan kesempatan
untuk mengembangkannya. Janganlah terlalu berharap bahwa Anda dapat
membahagiakan semua orang atau melakukan segalasesuatu sekaligus.
2.
Jangan memusuhi diri sendiri
Peperangan
terbesar dan paling melelahkan adalah peperangan yang terjadi dalam diri
sendiri. Sikap menyalahkan diri sendiri secara berlebihan merupakan pertanda
bahwa ada permusuhan dan peperangan antara harapan ideal dengan kenyataan diri
sejati (real self). Akibatnya, akan timbul kelelahan mental dan rasa frustrasi
yang dalam serta makin lemah dan negatif konsep dirinya.
3.
Berpikir positif dan rasional
“We are what
we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts, we make
the world” (The Buddha).
Jadi, semua itu banyak tergantung pada cara kita memandang segala sesuatbaik itu persoalan maupun terhadap seseorang. Jadi,
kendalikan pikiran kita jika pikiran itu mulai menyesatkan jiwa dan raga.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan
bahwa langkah membangun konsep diri adalah :
1.
Belajar menyukai diri sendiri atau cinta diri sendiri
2.
Kembangkan pikiran positive thinking
3.
Hubungan interpersonal harus dibina dengan baik
4.
Pro-aktif atau sikap yang aktif menuju yang positive
5.
Menjaga keseimbangan hidup
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Teori chaos menunjukkan
ketidakberaturan, kekacauan, keacakan atau kebetulan, yaitu: gerakan acak tanpa
tujuan, kegunaan atau prinsip tertentu. Dalam dunia pendidikan teori chaos ini
akan memberikan tantangan kepada pebelajar untuk lebih memahami pola-pola
pembelajaran yang timbul. Kondisi chaos membuat hilangnya kemampu-prakiraan
(predictability), karena adanya urutan atau susunan yang rumit yang
bertentangan dengan keteraturan.
Connectivism diperkenalkan pertama
kali oleh George Siemens. Connectivism merupakan teori pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip-prinsip yang digali melalui teori
chaos,
jejaring,
kompleksitas
(complexity), dan self-organizing.
Model pembelajaran connectivism merupakan model pembelajaran yang menekan pada
pengambilan keputusan secara cepat oleh siswa, kegiatan tersebut dibutuhkan
untuk melatih siswa dalam proses belajar mandiri di dalam maupun diluar kelas. Model pembelajaran connectivism mengarahkan siswa untuk mampu mengumpulkan
informasi-informasi yang dibutuhkannya dalam belajar secara cepat dan tepat,
dimana pada era digital saat ini infromasi telah banyak dapat diperoleh melalui
internet ataupun sumber lainnya.
B. Saran
Setelah membaca dan mempelajari tentang
makalah ini, penulis berharap pembaca mendapatkan tambahan ilmu tentang
bagaimana model pembelajaran connectivism. Makalah ini dibuat dari berbagai
sumber yang dirangkum menjadi sebuah materi tertulis, penulis menyadari bahwa
dalam pembuatan makalah ini masih terdapat adanya kekurangan dalam penyajian
materi sehingga penulis berharap para pembaca dapat memberikan masukan yang
membangun dalam penyempurnaan makalah ini. Penulis juga berharap agar para
pembaca dapat memperoleh infomasi ilmu terkait materi pada makalah ini melalui
sumber-sumber lain yang banyak beredar baik berupa buku maupun jurnal.
DAFTAR PUSTAKA
Kusmarni, Y. (2008). Teori Chaos: Sebuah Keteraturan Dalam Keacakan.
Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Muta'in. (2016). Model pembelajaran
connectivism untuk meningkatkan pemecahan masalah keterampilan belajar siswa di
MTs. Nurul Jadid Kota Mojokerto. Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam,
123-132.
N.Katherine Hayles. Chaos and Order: Complex Dynamics in Culture and Science (London:The University of
Chicago Press,Ltd.,1991), hlm. 171.





0 Comments